Ketika Kritik Kehilangan Substansi: Fenomena Populisme Retoris dalam Demokrasi
Ketika Kritik Kehilangan Substansi: Fenomena Populisme Retoris dalam Demokrasi
Oleh:
Halilintar Sutan Sulaiman
Ada satu ironi yang kian menonjol dalam praktik demokrasi kita hari ini: kritik semakin lantang, tetapi semakin miskin makna. Ia berseliweran di ruang publik dengan suara keras, diksi menggigit, dan ekspresi seolah paling bermoral, namun rapuh ketika diuji substansinya. Di balik hiruk-pikuk itu, berdirilah barisan pemikir yang mengklaim diri sebagai penjaga nurani publik, tetapi sesungguhnya terperangkap dalam ego, kerakusan simbolik, dan dahaga pengakuan yang tak pernah terpuaskan.
Kelompok ini gemar menyebut dirinya kritis, progresif, bahkan intelektual. Namun kritik yang mereka produksi tidak lahir dari kedalaman analisis, melainkan dari hasrat untuk selalu berada di pusat perhatian. Bagi mereka, kritik bukan lagi alat berpikir, melainkan alat eksistensi. Ia dipelihara bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi untuk memastikan bahwa nama, wajah, dan suaranya tetap beredar di ruang publik. Dalam logika semacam ini, substansi menjadi beban; yang utama adalah sensasi.
Ego menjadi fondasi utama gerakan mereka. Setiap kritik harus berangkat dari asumsi bahwa hanya merekalah pemilik kebenaran moral. Tidak ada ruang untuk kemungkinan bahwa kebijakan tertentu bisa saja tepat, atau bahwa pihak lain mungkin memiliki argumen yang sah. Segala sesuatu harus salah agar mereka tetap benar. Dalam dunia yang dibangun oleh ego semacam ini, dialog tidak pernah benar-benar diinginkan, sebab dialog mengandaikan kesetaraan nalar sementara yang mereka kejar adalah superioritas moral.
Kerakusan mereka bukanlah kerakusan materi, melainkan kerakusan simbolik. Rakus akan panggung, rakus akan sorotan, rakus akan status sebagai “pengkritik paling keras”. Mereka mengumpulkan kemarahan publik layaknya modal sosial. Setiap kegaduhan adalah investasi, setiap kontroversi adalah peluang menaikkan nilai diri. Kritik yang seharusnya berfungsi sebagai koreksi berubah menjadi komoditas diproduksi, dikemas, dan dijual demi popularitas.
Dalam praktiknya, kelompok ini tidak pernah puas. Ketidakpuasan bukanlah sikap kritis, melainkan kondisi permanen yang sengaja dipelihara. Sebab jika suatu masalah benar-benar selesai, maka alasan untuk berteriak akan hilang. Maka keberhasilan, sekecil apa pun, harus dicurigai; capaian harus dipelintir; perbaikan harus dikecilkan. Demokrasi yang sehat justru menjadi ancaman bagi mereka, karena demokrasi yang membaik tidak menyediakan cukup bahan bakar bagi retorika kemarahan.
Yang lebih problematis, populisme retoris yang mereka mainkan perlahan merusak kualitas berpikir publik. Emosi dikedepankan, nalar disingkirkan. Kompleksitas persoalan disederhanakan secara brutal, lalu dipresentasikan dalam bentuk slogan dan tudingan. Publik diajak marah, bukan memahami. Diajak membenci, bukan menimbang. Dalam situasi ini, kritik kehilangan daya pencerahnya dan berubah menjadi alat agitasi yang memiskinkan akal sehat bersama.
Demokrasi tentu membutuhkan kritik. Namun demokrasi tidak pernah membutuhkan pemikir yang rakus panggung dan haus validasi. Kritik yang lahir dari ego hanya akan melahirkan kebisingan, bukan perbaikan. Kritik yang lahir dari kerakusan simbolik hanya akan mempertebal polarisasi, bukan memperkuat deliberasi. Dan pemikir yang menjadikan kritik sebagai alat pemuasan diri pada akhirnya bukanlah penjaga demokrasi, melainkan parasit yang hidup dari kegaduhan demokrasi itu sendiri.
Pada titik inilah publik diuji. Apakah kita akan terus terpesona oleh suara paling keras, atau mulai belajar mendengar argumen paling masuk akal? Apakah kita akan terus memberi panggung pada kritik yang haus sorotan, atau mulai menuntut kritik yang berani bertanggung jawab? Sebab masa depan demokrasi tidak ditentukan oleh seberapa sering kritik diteriakkan, melainkan oleh seberapa jujur dan bernalar kritik itu disampaikan.








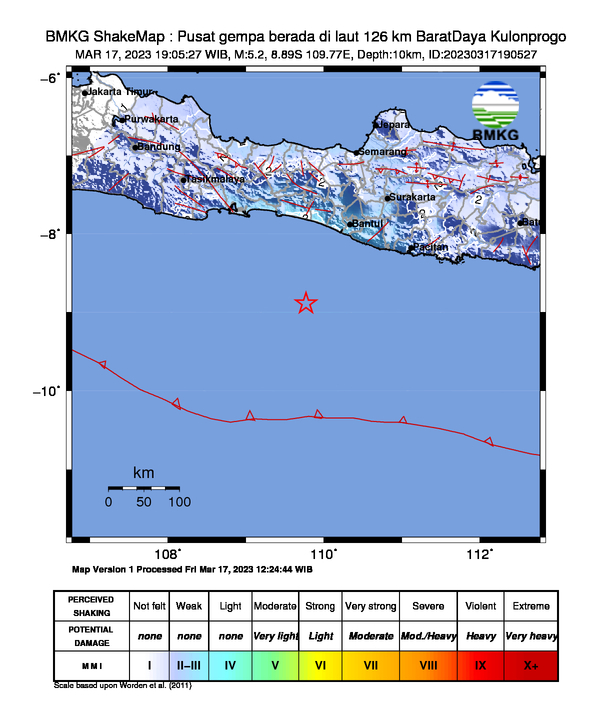
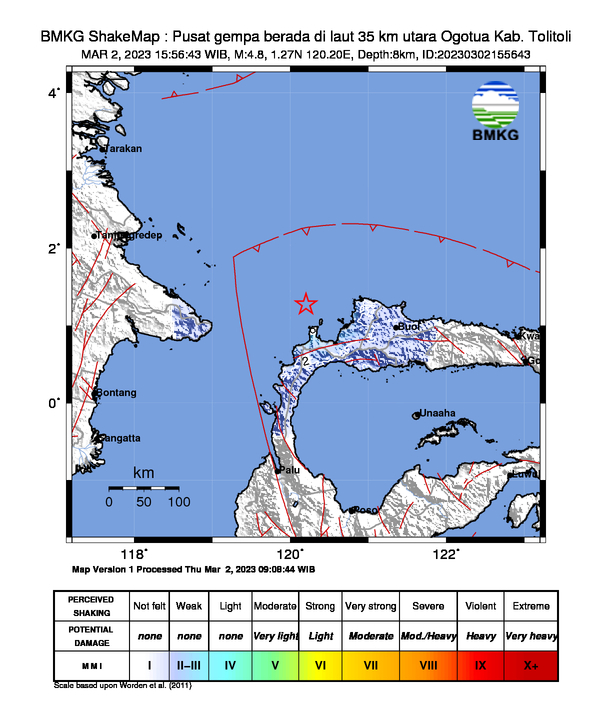





Tidak ada komentar